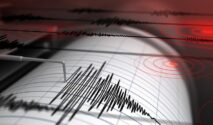Oleh : Chaironi Hidayat
Pagi selepas dhuha, masjid kecil di sudut kantor terasa teduh. Cahaya matahari menembus kisi-kisi rintik mendung, menimpa sajadah yang masih hangat oleh sujud duha. Udara di dalamnya hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar samar. Dalam keteduhan itu, sebuah kisah lama teringat dan tersampaikan kembali, kisah yang tak pernah usang, sebab diulang oleh hati setiap kali manusia merindukan teladan. Kisah tentang Nabi Muhammad Saw.
Beliau, setiap pagi dan sore, datang membawa makanan untuk seorang pengemis buta beragama Yahudi. Dengan sabar dan lembut, beliau menyuapkan makanan ke mulut lelaki tua itu. Namun lidah si pengemis tak berhenti mencela. Ia menuduh Muhammad sebagai tukang sihir, pengadu domba, pembawa kerusakan. Ia bahkan melaknat nama yang justru setiap hari membawanya pada kenyang. Ia tidak tahu, orang yang selalu hadir dengan tangan penuh cinta adalah sosok yang ia hina. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Tidak pernah berhenti datang. Tidak pernah berhenti memberi. Tidak pernah berhenti menyayangi.
Dari kisah itu, jelaslah: cinta Nabi melampaui sekat keyakinan, dinding prasangka, bahkan luka hati yang ditorehkan manusia kepadanya. Kasih sayang yang beliau hadirkan bukanlah kasih sayang bersyarat, bukan pula cinta yang menunggu balasan. Ia adalah mata air yang terus memancar, bahkan ketika batu menghantamnya. Semakin keras dunia mencoba melukai, semakin lembut pula beliau membalas dengan doa. Semakin dalam luka yang ditorehkan manusia, semakin luas pula samudra ampunannya membentang.
Dari kisah itu, teranglah sudah: cinta Nabi bukanlah cahaya yang dibatasi jendela sempit keyakinan, bukan pula api yang padam oleh tiupan prasangka. Ia menjelma pelukan luas yang merengkuh siapa saja, bahkan mereka yang pernah menaburkan garam di luka hatinya. Dalam kehangatan cinta itu, tidak ada wajah yang ditolak, tidak ada tangan yang dihindari. Semua disapa dengan kelembutan, semua direngkuh dengan rahmat. Kasih sayang beliau adalah angin yang berhembus tanpa memilih rumah mana yang akan disinggahi. Ia mengetuk hati yang keras, menyejukkan jiwa yang resah, dan menghidupkan kembali nurani yang nyaris padam. Seperti matahari yang menyinari tanpa membeda-bedakan, cinta Nabi hadir untuk semua, tak peduli apakah ia disambut dengan syukur atau ditanggapi dengan caci, kisah itu menjadi cermin bagi kita: betapa kecil cinta kita dibanding cinta beliau, betapa dangkal sabar kita dibanding sabar beliau. Sementara dunia mudah menumbuhkan dendam, beliau justru mengajarkan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang tetap mengalir, bahkan di tengah badai kebencian. Cinta Nabi adalah rahmat yang melintasi batas, pelajaran abadi bagi hati-hati yang ingin belajar menyalakan cahaya ketulusan.Saya teringat pula peristiwa hijrah. Kaum Anshar di Madinah menyambut para Muhajirin dengan dada terbuka. Mereka membagi rumah, tanah, pekerjaan, bahkan, dalam praktik zamannya, bersedia berbagi istri demi menjaga kelanjutan hidup saudaranya. Kini terdengar ekstrem, tetapi di sanalah saksi sejarah yang memperlihatkan betapa kasih sayang menyingkirkan rasa memiliki. Apa yang ada bukan lagi “milikku”, melainkan “milik kita.” Orang-orang luar Madinah yang menyaksikan kedekatan itu berkata lirih, penuh takjub: “Aku belum pernah melihat manusia mencintai orang lain sebagaimana sahabat Muhammad mencintai Muhammad.”
Cinta itu bukan sekadar penghormatan, bukan sekadar pengagungan. Ia adalah kerinduan yang tak ingin berpisah. Bahkan ada sahabat yang berucap: “Ya Rasul, aku ingin masuk surga hanya jika dapat bersamamu. Jika tidak, biarlah aku tidak masuk.”Beginilah cinta yang tak lagi mencari imbalan. Ia menjelma sebagai ikatan yang melampaui hidup dan mati, dunia dan akhirat.
Kemudian ingatan beralih kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi, sosok yang keras seperti baja yang ditempa api, seorang lelaki padang pasir yang disegani karena keberaniannya memburu singa di tengah sunyi gurun. Ketegasannya dahulu membuat namanya bergetar di telinga banyak orang. Namun lihatlah, ketika Islam mengetuk pintu hatinya, bara yang dahulu menyala sebagai amarah berubah menjadi cahaya yang teduh. Dari lelaki yang tegas, ia menjelma pemimpin yang lembut, seorang khalifah yang menundukkan kekuasaan di hadapan kasih. Ukurannya sederhana, namun menghunjam: jika seorang pejabat tak mampu menyayangi istri dan anak-anaknya, bagaimana mungkin ia bisa menyayangi rakyat? Umar menimbang kepemimpinan bukan dari jubah kebesaran, bukan dari gelar atau jabatan, melainkan dari cinta yang hidup di dalam rumah. Baginya, rumah adalah cermin kekuasaan: bila congkak dan angkuh di hadapan keluarga, bagaimana mungkin ia bisa adil dan rendah hati di hadapan rakyat? Karena itu, Umar tanpa ragu memecat pejabat yang gagal menanam kasih di rumahnya sendiri, sebab kepemimpinan sejati lahir dari kelembutan, bukan dari teriakan kuasa.
Dan demikianlah Umar bin Khattab berdiri sebagai teladan: keras pada kezaliman, namun lembut pada rakyatnya; tegas pada pengkhianatan, namun penuh kasih kepada yang lemah. Ia memahami bahwa seorang pemimpin bukanlah singa yang menerkam, melainkan pohon yang menaungi. Dari tangannya, lahir keadilan yang berakar pada cinta. Dari hatinya, mengalir kasih sayang yang menyejukkan negeri. Dalam dirinya, kekuatan dan kelembutan bersatu, menjadi pelajaran abadi bahwa kuasa tanpa kasih hanyalah tirani, sementara kasih tanpa kuasa hanyalah impian. Umar menghadirkan keduanya, dan dengan itu, sejarah mengenangnya sebagai pemimpin yang dibangun dari cinta yang kokoh.Ada paradoks yang indah: manusia yang dulu dikenal tegas dan garang justru menjadi lambang welas asih setelah mengenal Nabi. Kasih sayang mampu menundukkan kekerasan, sebagaimana air menundukkan api.
Semua kisah itu menyadarkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan tambahan dalam kehidupan, melainkan inti. Kantor tanpa kasih hanyalah mesin berisik yang menggiling manusia. Ibadah tanpa kasih hanyalah gerakan tubuh tanpa jiwa. Hidup tanpa kasih hanyalah rutinitas yang perlahan melahirkan kehampaan.
Allah sendiri mengajarkan doa lembut di ujung surah Al-Baqarah:
*“Rabbana la tu’akhidzna in nasina aw akhta’na…”*
“Ya Allah, jika kami lupa atau salah, janganlah Engkau siksa kami.”
Doa itu sederhana, tetapi mengandung pengakuan paling jujur: bahwa manusia lemah, sering lalai, mudah keliru. Dan Allah, dengan kasih sayang-Nya, memilih untuk memaafkan. Rasulullah pun sangat menyukai doa itu, karena ia menggambarkan betapa Tuhan lebih memilih mengampuni daripada menghukum. Maka bukankah kita pun seharusnya demikian? Lebih memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Lebih memilih merangkul daripada menolak. Lebih memilih menyayangi daripada membenci.
Seandainya kasih sayang dijadikan pedoman, mungkin kita tak perlu banyak undang-undang, tak perlu aturan yang mengekang. Karena hati yang dipenuhi kasih akan lebih taat daripada sekian banyak pasal dan pasal. Ia akan menjaga tangan dari menyakiti, menjaga lidah dari menyakiti, menjaga langkah dari merugikan. Ia adalah pagar tak kasatmata yang lebih kokoh daripada tembok penjara. Maka tinggal kita, manusia-manusia hari ini, yang perlu menjawab: apakah mau melanjutkan teladan itu? Apakah kita rela menjadikan kasih sayang sebagai nafas yang mengiringi setiap detik kehidupan? Jika iya, dunia akan menjadi taman yang lebih hijau, hati akan menjadi telaga yang lebih jernih, dan jiwa-jiwa akan menemukan rumahnya dalam damai. Sebab kasih sayang adalah cermin dari rahmat Ilahi, yang diturunkan untuk meliputi seluruh alam.Pagi itu, di masjid kecil yang sederhana, saya merasa sedang belajar ulang menjadi manusia. Bukan manusia yang hanya pandai bekerja. Bukan manusia yang hanya rajin beribadah. Melainkan manusia yang tahu bagaimana caranya mencintai. Kasih sayang, ternyata, adalah jantung kehidupan. Ia bukan sekadar bunga di pinggir jalan yang mudah dipetik dan mudah layu. Ia adalah akar yang menancap dalam, memberi napas pada setiap helai daun kehidupan. Dan mungkin, pada akhirnya, hanya kasih sayanglah yang akan kita bawa pulang. Segala harta, kedudukan, ilmu, prestasi, semua akan ditinggal. Tetapi kasih sayang yang pernah kita taburkan, akan kembali kepada kita. Ia menjadi cahaya yang tidak padam, meski matahari dunia telah lama tenggelam.
Di masjid kecil sederhana, dengan dinding-dindingnya yang penuh bekas sujud dan udara harum oleh doa, saya merasa sedang belajar ulang menjadi manusia. Bukan manusia yang hanya pandai bekerja, mengejar angka dan prestasi, lalu pulang dengan dada kosong. Bukan pula manusia yang hanya rajin beribadah dengan bibir yang bergetar melafalkan doa, sementara hatinya masih beku dan keras. Tetapi manusia yang benar-benar mengerti bagaimana caranya mencintai—mencintai tanpa syarat, tanpa hitungan untung-rugi, mencintai dengan hati yang lapang seperti langit. Kasih sayang, ternyata, adalah jantung kehidupan. Ia bukan sekadar bunga di pinggir jalan yang mudah dipetik lalu mudah layu. Ia adalah akar yang menancap dalam, yang diam-diam memberi napas pada setiap helai daun kehidupan. Tanpa akar itu, pohon akan mati; tanpa kasih sayang, manusia hanya tinggal raga yang kering. Kasih sayanglah yang menjadikan rumah terasa rumah, pekerjaan terasa ibadah, dan ibadah terasa hidup.
Di bawah kubah masjid Kementerian Agama, kita memahami bahwa kasih sayang adalah perpanjangan tangan dari rahmat Allah. Ia mengalir melalui tatapan lembut seorang ibu, melalui genggaman tangan seorang sahabat, melalui maaf yang diberikan kepada orang yang pernah melukai. Ia adalah bahasa ilahi yang diturunkan agar manusia tak hidup sebagai serigala yang memangsa, tetapi sebagai saudara yang saling menguatkan. Kasih sayang juga adalah cermin dari ibadah sejati. Sujud tanpa kasih sayang hanya menyentuh lantai, bukan menyentuh langit. Zikir tanpa kasih sayang hanya bunyi bibir, bukan cahaya yang menenangkan. Ilmu tanpa kasih sayang hanyalah pedang yang tajam, bukan lentera yang menerangi. Maka, belajar mencintai sesama adalah bagian dari belajar mencintai Sang Pencipta.
Di masjid kecil itu, kita seakan diajak untuk menanam kembali akar-akar kasih sayang dalam hati sendiri. Agar doa-doa tak hanya melangit, tetapi juga menetes menjadi air sejuk bagi sesama. Agar kerja tak hanya menghasilkan harta, tetapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Agar hidup tak hanya panjang diukur waktu, tetapi dalam diukur kasih. Sebab pada akhirnya, kasih sayang adalah detak yang membuat kehidupan terus berdiri dan tanpa kasih, hidup hanyalah bayangan yang kosong.
Kasih sayang adalah bahasa universal, yang dimengerti siapa saja tanpa perlu diterjemahkan. Ia merayap halus menembus batas agama, bangsa, dan pandangan hidup. Anak kecil merasakannya dari senyum ibunya. Seorang asing merasakannya dari uluran tangan yang tak ia duga. Bahkan musuh sekalipun dapat luluh ketika dihadapkan pada kasih sayang yang tulus. Nabi telah mencontohkan: beliau berdoa untuk mereka yang menyakitinya, beliau tersenyum kepada mereka yang memusuhinya. Para sahabat meneladani: Umar yang keras menjadi lembut, Abu Bakar yang penuh welas asih menjadi sandaran umat, Ali yang penuh hikmah menebarkan ilmu bersama kasih.
Duha pagi, 29 Agustus 2025